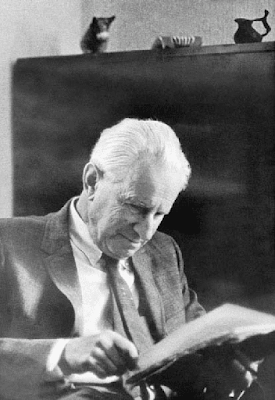 |
Herbert Marcuse
Salah satu pendiri Mazhab
Frankfurt
Dikenal melalui bukunya ”One
Dimensional Man”
|
PERTAMA, kritik hak milik ekonomi politik Marx yang mengalami pergeseran dari motif kelas menjadi motif psikologi. Pendasaran segregasi kelas yang menjadi acuan marxisme dalam menelusuri motifmotif penguasaan, di tangan pemikirMazhab Frankfurt malah mengalami penurunan ketajaman dalam menganalisis keadaan objektif masyarakat. Apabila Marx melihat asalusul penindasan secara objektif ditemukan dalam pembagian kelas masyarakat, di mana penguasaan alat produksi oleh kaum borjuasi menjadi sumber penghisapan, melalui cara pandang Mazhab Frankfurt malah dikembalikan kepada unsurunsur subjektif berupa dorongandorongan intrinsik manusia. Akibatnya, kritik Marx yang semula ditujukan kepada analisaanalisa idealistik, justru di tangan Mazhab Frankfurt terjadi repetisi atas apa yang telah Marx kritik sebelumnya.
Kedua,
dalam kajian Mazhab frankfurt, pendasaran marxisme terhadap kelas buruh
tak lagi mendapatkan tekanan seperti yang diharapkan Marx. Telah diketahui
sebelumnya, pendakuan Marx bahwa setiap kelas bertindak atas dasar
kepentingannya, dan kepentingannya ditentukan oleh situasi objektifnya,
menjadi semacam pintu masuk untuk memahami pertentangan kelas yang
terjadi di dalam masyarakat kapitalis. Melalui cara ini berdasarkan kepentingan
objektif yang ditentukan oleh kedudukan kelas, menuntut suatu sikap mawas diri
demi menjaga eksistensi masingmasing kelas. Karena sikap inilah terjadi
pertentangan kelas yang menjadi inti dari gerak masyarakat. Sebab itulah
seperti yang ditekankan di dalam Manisfesto Komunis perlunya
kesadaran kelas untuk mempertahankan kepentingan kelas buruh yang banyak
mengalami tekanan dari kelas di atasnya. Sikap konservatif kelas borjuis
yang merupakan konsekuensi dari kedudukan objektifnya di masyarakat, mau tak
mau harus berhadapan langsung dengan kelas pekerja yang memiliki semangat progresif
dan revoulusioner akibat dari kepentingan kelas yang bertahan di antara
keduanya.
Sementara
itu, akibat pembacaan yang meluas, serta beragam teoritisi yang terlibat di
dalamnya, Mazhab Frankfurt sulit mendefenitifkan keberpihakannya
kepada kelas pekerja seperti dalam pemikiran Marx. Perhatianya yang meluas
terhadap musik, budaya, media massa, mode, dan sebagainya yang dinyatakan
sebagai industri budaya, mengakibatkan sulitnya mempertahankan pembacaan
sekaligus kritik ekopol marxian yang menjadi cara pandang
utama dalam tradisi marxis. Akibat lunturnya kepercayaan Mazhab Frankfurt
kepada kelas pekerja, di saat yang bersamaan bergerak memasuki segmentasi
kelaskelas yang lain semisal kaum radikal terdidik di kampuskampus sebagai agen
perubahan.
Ketiga,
penyematan label revisionisme yang diberikan pemikir marxis ortodoks,
membuat Mazhab Frankurt sulit mendapatkan simpati dari gerakan kiri yang
masih percaya terhadap metode pembacaan ekopol Marx. Walaupun
dikatakan oleh para tokohnya bahwa usaha yang dikerjakan Mazhab Frankfurt
merupakan bagian dari usaha krirtik yang pernah dilakukan Marx terhadap
kapitalisme, tetap saja di luar pandangan mereka, mazhab Frankurt dinyatakan
sebagai suatu aliran yang keluar dari tradisi pemikiran marxis.
Di
sini, perlu dijelaskan sepintas mengenai tiga tradisi atau pendekatan
seputar metode pembacaan terhadap Das Capital Marx yang sampai
hari ini masih berlangsung, yang dikemukakan oleh Harry Cleaver. Pertama,
tradisi ekonomi politik. Pendekatan tradisi ini mesti dipahami pada
konteks International II berlangsung (1889-1916). Problemnya berkisar
pada persoalan determinasi ekonomi dan teks acuannya, tentu saja, adalah Contribution
to a Critique of Political Economy, di mana Marx berbicara tentang relasi
ekonomi sebagai basis masyarakat yang darinya muncul bangunan suprastruktur
yang bersifat legal politis. Dalam konteks ini terjadi perdebatan antara
Edduart Bernstein dengan Rosa Luxemburg tentang apakah krisis ekonomi yang akan
menumbangkan kapitalisme itu niscaya atau tidak. Melalui bukunya Evolutionary
Socialism, Bernstein mengajukan pendapat bahwa krisis itu tidak niscaya
menghancurkan kapitalisme, krisis itu hanya akan memperlambat akumulasi kapital
sementara kaum kapitalis akan dapat mengkonsolidasikan diri menghindari krisis
ini. Maka itu bagi Bernstein perjuangan yang mesti dilancarkan melawan kaum
kapitalis adalah perjuangan ekonomi seraya menggabungkan diri ke dalam
parlemen.
Hasil
pembacaan Bernstein atas Kapital ini segera dilawan oleh Rosa
Luxemburg dalam Reformasi atau Revolusi (1900) dan Akumulasi
Kapital (1913). Luxemburg menyatakan bahwa krisis kapitalisme tak
terhindarkan justru, berkebalikan dengan Bernstein, karena akumulasi kapital
akan memuncak dalam konflik antar negara. Berdasarkan pengertian ini, Luxemburg
memberikan solusi yang berbeda, yakni persiapan revolusi dan penolakan atas
sekedar reformasi. Keduanya mewakili posisi dasar pembacaan ekonomi politik
atas Das Capital yang akan membayangi para penafsir
selanjutnya. Penekanan Bernstein pada reformasi gradual melalui jalur
intra-parlementer (dan karenanya lebih dekat dengan tendensi sosial-demokrat)
akan diteruskan oleh Karl Kautsky, Rudolf Hilderling, Otto Bauer, Fritz
Sternberg, sementara ketidakpercayaan Luxemburg pada perjuangan ekonomi-parlementer
dan penekanannya pada revolusi atau jalur ekstra-parlementer akan diteruskan
oleh Lenin, Anton Pannekoek dan Paul Mattick.
Sementara
di luar konteks internasional kedua, terutama disekitar tahun 1940/50an,
berkembang tipe pemikiran yang berusaha mensintesakan kritik ekopol Marx dengan
teoriteori yang diajukan Keynes. Tradisi pemikiran ini berkembang di dunia
Anglo-Amerika, yakni neo-marxis keynesian. Tokoh-tokohnya adalah Michael
Kalecki, Joan Robinson, Paul Sweezy dan Paul Baran. Menurut tradisi ini,
pendekatan ekopol Marx yang tertuang dalam Das Capital memiliki
beberapa kekurangan terhadap situasi perkembangan kapitalisme. Sebab itulah,
mereka berusaha mengkombain dengan memasukkan pembacaan Keynesian terhadap
analisis ekopol marxis. Model pembacaan yang demikian
akhirnya menjauhkan tradisi ini dengan sendirinya dari kritik Marx yang
bersandar pada suatu analisis yang hanya mencomot beberapa analisis Marx.
Dalam perkembangannya, tradisi inilah yang menginisiasi lahirnya gerakan kiri
baru (new left movement) Eropa di sekira tahun 6oan.
Yang kedua adalah
tradisi filsafat. Cleavert membaginya menjadi dua, yakni tradisi yang
dikembangkan oleh Louis Althusser bersama muridmuridnya (Balibar hingga
Badiou) dan yang kedua adalah revisionisme yang menjadi bagian di dalamnya
yakni, Marxisme Barat (Western Marxism): György Lukács, Antonio
Gramsci, Karl Korsch—semuanya menekankan pengaruh Hegel
dalam Marx, Marxis Neo-Kantian: Galvano, Delavolpe dan Lucio Colletti,
Marxis-Hegelianisme: Alexandre Kojéve dan Jean Hyppolite, Marxis-eksistensialisme: JeanPaul
Sartre, Simone de Beauvoir dan Maurice Merleau-Ponty. Marxisme
fenomenologis: Tran Duc Thao dan Karel Kosik, Teori Kritis Mazhab Frankfurt:
Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin dan Jürgen
Habermas.
Oleh
Cleaver, pembagian kubu ortodoks dan revisionis ini dijelaskan melalui dua
tendensi yang berbeda: sementara Althusser mencoba menghidupkan kembali doktrin
diamat (dialectical materialism) melalui pembacaan atas Kapital,
Mazhab Frankfurt dan tendensi Marxisme Barat justru mengutamakan peran
kebudayaan dalam analisis Marxis. Diamat versus kulturalisme—pertentangan
inilah yang menerangkan dasar perbedaan posisi antara Marxis ortodoks dan
Marxis revisionis.
Tendensi
kulturalisme yang banyak dikembangkan Mazhab Frankfurt disebutkan Cleavert
akibat ketokohan Friedrich Polloch. Melalui bukunya Automation,
Pollock memperlihatkan adanya kecenderungan akumulasi kapital oleh kapitalisme
negara dan negara otoritarian yang menyebabkan perluasan penghisapan
kapitalisme di seluruh sendisendi kehidupan masyarakat. Pendektannya yang
memperlihatkan perluasan penghisapan kapitalisme dari pabrikpabrik menuju
masyarakat yang lebih luas, mengakibatkan adanya indikasi suatu pembacaan
masyarakat yang lebih luas dari hanya sekedar penjelasan ekopol marxis. Menurut
Cleavert dari sinilah bermula adanya pembacaan kultural yang menjadi pembacaan
dominan atas masyarakat di dalam tradisi pemikiran Mazhab Frankfurt.
Tradisi
yang ketiga adalah pendekatan politis seperti yang ditokohkan Lenin.
Tradisi ini berputar dalam problem perlunya pendekatan secara strategis dan
taktis untuk mewadahi perjuangan kaum proletariat. Seperti yang
dituliskannya dalamWhat Is to be Done?, Lenin menganjurkan betapa
pentingnya membangun partai payung dengan kemampuan disiplin yang tinggi untuk
melakukan perjuangan. Partai garis depan ini, disebutkan Lenin adalah partai
yang bertujuan merangkum seluruh gerakangerakan buruh di dunia. Hanya lewat
cara inilah Lenin berkeyakinan revolusi dapat dimungkinkan.
Keempat,
peralihan penekanan kritik yang diajukan Jurgen Habermas melalui rasionalitas
komunikatifnya, memberikan efek yang berbeda dari intuisi marxisme yang semula
bersifat radikal dan revolusioner. Pendekatan komunkatif yang diajukan Habermas
sebagai jalan keluar persitengangan antara marxisme dan kapitalisme, malah
menjadi suatu pendekatan yang mengabaikan unsurunsur di luar dari komunikasi
itu sendiri. Pengandaian Habermas bahwa di dalam tindakan komunikasi dengan
sendirinya akan menetralkan suatu posisi dan kepentingan, justru tidak bekerja
seperti yang diharapkannya di dalam level praktik. Komunikasi yang disebutnya
sebagai tindakan praktis, malah justru menguatkan posisi dari awal bagaimana
kepentingan kelas borjuis bekerja untuk mendominasi kelas proletariat.
Wacanawacana yang dikembangkan kelas borjuis melalui tindakan komunikasi justru
kembali melanggengkan kepentingan melalui subordinasi pengetahuan yang
dimilikinya.
Kelima, Cakupan
dan rentang penelitian yang luas dari orang-orang yang terlibat dalam Mazhab
Frankfurt dinilai sebagai perkembangan yang inkonsisten dengan rancangan awal
proyek mereka, dan inkonsistensi ini dianggap sebagai kelemahan paling mendasar
dari Teori Kritis. Para pendukung Cultural Studies menuduh bahwa terdapat
indikasi kesukaan Mazhab Frankfurt pada “budaya tinggi”, walau gagasan Mazhab
Frankfurt juga menjadi inspirasi dan dipraktekkan oleh para environmentalis dan
teoretisi teknologi dan alam seperti SF Schumacher.
