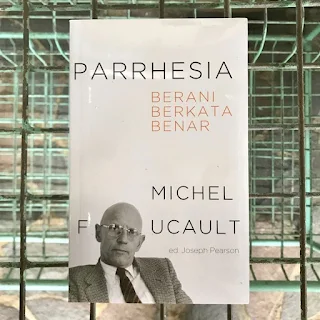Ini bocoran saja: dua hari lalu
saya didadak Sulhan Yusuf agar segera meresensi buku teranyar dari salah satu desa
di Bantaeng --kabupaten di Sulawesi yang mencuri perhatian kita 1 dekade
belakangan--"Literasi Dari Desa Labbo". Buku kumpulan tulisan yang
tempo hari sudah saya ketahui cikal bakal kedatangannya. Tapi, berhubung masih
diikat kesibukan lain, saya akhirnya baru bisa menulis ini di sela-sela
pertemuan akhir kelas kuliah yang saya ampu. Sembari memberikan final
mahasiswa, saya mencuri waktu agar tulisan yang dibuat ini dapat rampung dan
dinikmati sesuai pesanan.
Bukan rahasia lagi, cara untuk
mengapresiasi buku-buku yang diterbitkan orang-orang dekat atau komunitas yang
sevisi, kami-kami sering saling "memesan", saling mendukung, dan juga
saling menyemangati entah dengan cara apa. Resensi ini salah satu wujudnya.
Saya yakin di balik terbitnya buku
ini, "pesanan" adalah kekuatannya. Seperti dituliskan dari catatan
penyunting, buku ini lahir atas dasar inisiatif warga Desa Labbo yang ingin
mengabadikan ingatan, pengamatan, dan pengalamannya mengenai apa saja yang berkaitan
dengan Desa Labbo.
"Buku ini merupakan hasil dari
proses panjang aktivitas literasi di Desa Labbo, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi
Selatan. Sejak kepala desa dijabat oleh Subhan Yakub, saya sudah ikut mendorong
program-program literasi yang dicanangkan Pemerintah Desa Labbo, mulai dari
pembenahan perpustakaan desa hingga pelatihan literasi untuk Karang
Taruna."
Di atas, kutipan saya ambil untuk
membunyikan makna "pesanan" yang dimaksud. Yakni hasil kalkulasi
tukar tambah pengetahuan dan pengalaman dari siapa pun yang terlibat dari
macam-macam kegiatan di atas.
Mulai dari kepala desa, kepala
dusun, mahasiswa, ibu rumah tangga, aktivis, pendamping desa, dan warga desa,
adalah orang-orang yang gotong royong mengafirmasi "pesanan" dari
aktivitas bermatra literasi.
Dengan kata lain,
"pesanan" itu berwujud pemberdayaan dari desa, oleh desa, dan untuk
desa. Ya, buku ini bisa dibilang adalah hasil rembukan warga desa untuk
menghasilkan sesuatu bagi desa mereka.
Itulah sebabnya, kalau ada yang
mengetahui gerak-gerik para penulis di buku ini, mereka bergerak atas
"pesanan" yang sama, visi yang sama, dan beruntungngnya bisa bertahan
dalam frekuensi yang sejajar.
Mereka, walaupun datang dari
beragam profesi, latar belakang pendidikan berbeda, usia, dan kecenderungan
politik yang saling membelakangi, bisa demikian kejadiannya karena lahir dari
hasil ijtimak bersama: menerbitkan buku.
Dari sisi ini, imajinasi tentang
desa mesti digugat. Kadang desa diidentikkan terbelakang, tidak dinamis, dan
sulit berkembang. Bahkan, desa dari kacamata ilmu-ilmu sosial mainstream,
didudukkan sebagai lokasi pinggiran dengan kota sebagai pusatnya. Sebab dari
itu, desa selalu dipandang wilayah yang tidak layak diperjuangkan dan tidak
mesti diprioritaskan.
Hadirnya buku ini ibarat gugatan
tentang semua itu. Bukan padi, buah-buahan, atau hasil ternak saja, melainkan
buku sebagai penanda signifikan yang menjadi catatan kritis mengenai pergeseran
aktivitas warga desa.
Buku yang identik bagi kalangan
terdidik, di Desa Labbo diusahakan menjadi lebih liberal lagi. Ia didudukkan
sama dengan sawah, kebun, dan ladang sebagai area atau benda yang menjadi pusat
pikiran warga desa.
Seketika warga desa bertransformasi
bukan saja akrab dengan perkakas pertanian dan perkebunan, tapi juga dengan laptop,
jaringan wifi, buku, jurnal, catatan koran, laporan desa, dan siaran televisi
yang semuanya menjadi semesta baru membentuk wacana di keseharian mereka.
Dengan kata lain, sebagian warga
desa yang akrab dengan pekerjaan-pekerjaan tanah, berubah ikut naik ke
ketinggian bagaimana mengabsraksi ide dan gagasan dalam dunia literasi
--sesuatu yang demikian jauh dari keseharian mereka.
Berkat itu semua, Desa Labbo
berhasil meraih penghargaan Perpustakaan Desa terbaik dari seluruh perpustakaan
desa se-Tanah Air. Tentu ini hanya salah satu program dari sekian banyak
program desa yang bergerak dengan visi literasi.
Sekarang konteks masyarakat desa
tidak jauh berbeda keadaannya dengan masyarakat kota, para kontributor di buku
ini masih mempertahankan oleh apa yang disebut sosiolog Prancis, Emile Durkeim
sebagai "kesadaran kolektif". Ihwal inilah yang memandu hal-hal di
atas dapat mewujud menjadi satu buku seperti ini.
Patut dicurigai jangan-jangan warga
kota sudah tidak mampu lagi memiliki kemampuan seperti warga Desa Labbo. Selain
berwatak individualis dan dinamisnya aktifitas profesi, sulit rasanya
membayangkan, satu kelurahan, misalnya, mau keluar sejenak dari spekulatifya
hidup kiwari demi melakukan kerja kultural semacam menerbitkan buku.
Di sisi ini kita mesti mengacungi
jempol buat warga Desa Labbo. Kendati tidak semua, mereka yang menulis untuk
buku ini telah memosisikan dirinya sebagai figur-figur publik, walaupun untuk
desa mereka saja. Figur publik di sini, tentu mereka yang mengedepankan urusan
umum sebagai urusan pribadi mereka.
Dengan kata lain, mereka bekerja
dan menulis tentu untuk kemajuan bersama. Kemajuan Desa Labbo sendiri.
Walaupun tema tulisan buku ini
macam-macam, tapi barangkali kecintaan terhadap desa mereka-lah sehingga buku
ini dapat terbit di hadapan khalayak. Itulah sebabnya, sulit menemukan narasi
yang mampu mengikat keseluruhan dan keberagaman tulisan di buku ini yang juga
mengikutkan fiksi di dalamnya.
Literasi Dari Desa Labbo terdiri16
artikel, 16 esai, 11 cerita, 4 puisi. Editor atau penyunting buku ini,
barangkali sedikit kesulitan mengkamar-kamarkan baik genre, tema, isi dan jenis
tulisan dalam buku ini. Dari sisi ini mungkin pembaca bisa menilai dan
mengkritisinya, bahwa akan jauh lebih baik jika sebuah buku mesti berdiri di
dalam satu genre tulisan saja.
Satu hal yang pasti, kehadiran buku
ini yang merupakan buah tangan langsung para warga Desa Labbo, walaupun
sifatnya tidak umum, adalah gejala tersendiri bahwa di desa-desa sekarang,
terutama di Sulawesi Selatan, tengah terjadi perubahan senyap memformulasikan
ulang modal utama apa yang bisa dimaksimalkan di desa bersangkutan. Uniknya
semua itu tidak lagi didasakan kepada tradisi lisan, sesuatu yang khas
masyarakat desa, melainkan beralih menjadi tradisi tulisan.
Perubahan tradisi keberaksaraan ini
besar kemungkinan akan mengubah pola pikiran, sumber daya, mengikut hasil-hasil
apa saja yang lahir dari potensi desa. Bukan lagi hasil-hasil bumi saja, tapi
bisa saja bakal lahir potensi lain yang lebih besar karena ditunjang dengan
kegiatan-kegiatan literasi.
Dilihat dari sisi ini, walaupun
demikian masih jauh, kegiatan literasi adalah salah satu syarat terjadinya
transformasi masyarakat agar lebih maju dan kreatif. Merupakan teka-teki, apa
yang nanti bakal terjadi, bukan saja di Sulawesi saja, jika semua desa di
Indonesia bergeliat yang sama seperti Desa Labbo. Menarik mengamati
perkembanganya.
Terakhir, jika Anda sudah sampai di
bagian ini, Anda bakal mengerti bahwa tulisan ini bukanlah sepenuhnya resensi.
Biarlah pembaca lain yang melakukannya, atau warga Desa Labbo sendiri yang
mengisi tugas itu. Tulisan ini hanya berusaha menempatkan dirinya pada
keberpihakan yang sama, bahwa --meminjam istilah Alwy Rachman-- gerak-gerik
perababan yang baik, tidak dimulai kecuali dari aktifitas literasi di dalamnya.
Ihwal yang menjadi modal sejarah Bugis-Makassar, seperti sudah kita ketahui
selama ini.
Judul : Literasi dari Desa
Labbo
Penulis
: Sulhan Yusuf, dkk.
Penerbit : Liblitera
Edisi : Pertama, Desember 2018
Tebal : 374 hal
ISBN : 9786026646170