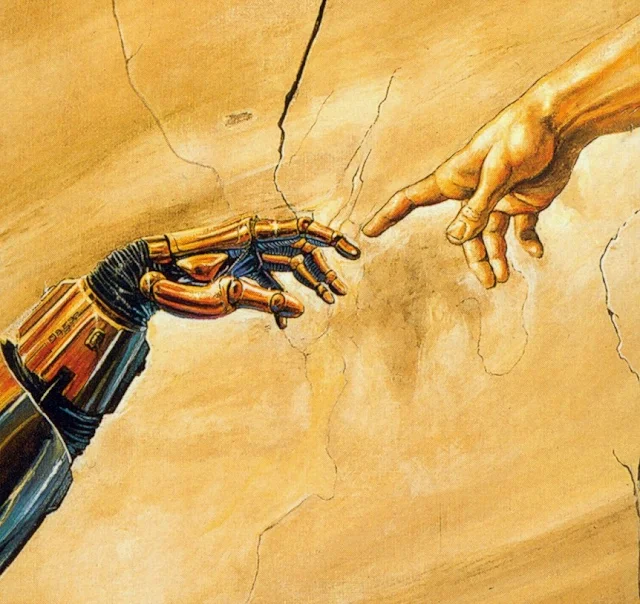“Barangsiapa yang menghancurkan
buku bagus ia sedang membunuh rasio itu sendiri…” John Milton, penyair Inggris.
Entah apa yang dikhawatirkan dari sebuah buku, selain daripada kemampuannya menggerakkan orang-orang. Di masa-masa ilmu pengetahuan masih kalah andil dari doktrin kekuasaan, buku seolah-olah benda haram jadah yang mesti dibumihanguskan.
Dalam buku Penghancuran Buku dari Masa ke Masa karangan Fernando Báez, dijelaskan tindakan bibliosida dapat ditarik jauh di belakang sejarah umat manusia. Uniknya tindakan penghancuran buku ini malah mengetengahkan sisi paradoksal dari sebuah peradaban yang kerap diafirmasi secara positif. Catatan Báez banyak mengungkap kemajuan suatu peradaban lebih banyak berdiri di atas sisa-sisa debu pagina buku.
Di alaf peradaban Barat misalnya, bibliosida kerap berjalan bersisian dengan gerakan misionarisme gereja. Saat itu, buku mengalami nasib tarik ulur perebutan yang berpangkal dari dua cara pandang.
Dalam hal ini, tentu saat itu cara pandang yang absah menyangkut kebenaran dan moral berasal dari paradigma keimanan yang disetujui pihak gereja. Dengan kata lain, extra ecclesiam nulla salus (tiada keselamatan di luar gereja) sebagai doktrin iman dari gereja saat itu, juga berarti berlaku bagi seluruh teks-teks di luar injil sebagai kepustakaan yang dilarang beredar karena tidak dianggap sebagai representasi pengetahuan yang absah bagi jalan keselamatan.
Itu artinya seluruh teks atau kitab yang tidak masuk dalam kategori “stempel” gereja, mesti dienyahkan dari lalu lintas pengetahuan masyarakat.
Untuk mengantisipasi ini, dalam sejarahnya, pihak gereja bukan sekadar bertindak sebagai institusi agama belaka, tapi berubah menjadi institusi koersif semimiliter dengan mengeluarkan daftar panjang buku-buku yang dipandang menyebarkan bid’ah dan kesesatan di tengah masyarakat.
Bagi masyarakat Islam, novel Animal Farm karya George Orwell di Uni Arab Emirat sejak 2002 menjadi buku terlarang. Alasan penolakan pemerintah negara itu lucu sekaligus keblinger, hanya karena salah satunya, menampilkan sesosok babi yang dapat berbicara. Menurut pengakuan pemerintah bersangkutan, buku itu bertentangan dengan spirit dan nilai-nilai Islam.
Tapi, siapa pun tahu, apa yang sebenarnya menjadi ide utama buku bernuansa politik perlawanan itu. Mungkin saja, penolakan pemerintah semisal yang terjadi di Uni Emirat Arab, lebih ditentukan oleh alasan ideologis berupa kekhawatiran terhadap naiknya taraf kesadaran rakyat seperti cerita di novel itu.
Di Iran, jangan sekali-kali membaca karya-karya Salman Rushdie sepertil Mildnight’s Children, atau The Satanic Verse. Ketika ketahuan, Anda seketika bisa berhadapan dengan pihak berwenang. Sudah sejak dari era Imam Khomeini buku-buku Salman Rusdhie dilarang dibaca karena, terutama The Satanic Verse, mengandung olok-olok terhadap figur suci Rasulullah. Karena itu, si empunya bersuaka ke luar negeri setelah difatwakan hukuman mati.
The Monument Men’s (2014) film yang cocok menyatakan bahwa keberlangsungan sejarah manusia tidak akan bisa maju pesat jika ia kehilangan benda-benda bernilai tinggi berupa karya tulis dan kesenian.
Film ini dibintangi George Clooney, Matt Damon, Bill Murray dan beberapa aktor Hollywood lainnya, yang mengungkap suatu ambisi kekuasaan yang ingin menguasai dunia dengan cara membumihanguskan peninggalan-peninggalan kebudayaan, berupa karya patung, karya tulis, dan lukisan dengan cara dibakar.
Ya, film ini mengambil konteks sejarah yang benar-benar terjadi ketika Hitler kesetanan ingin menduduki, jika tidak seluruh dunia, maka seluruh wilayah Eropa. Kegiatan antikebudayaan dengan dalih membangun kebudayaan baru ini, persis seperti perlakuan Kaisar Nero, raja Romawi ke-5 yang gemar membakar bangunan-bangunan vital negeri serbuan yang berhubungan dengan maju mundurnnya kebudayaan negeri bersangkutan.
Seolah-olah menemukan dalil historisnya, diceritakan melalui film itu, Hitler menggunakan badan-badan kebudayaan yang ditopang dengan kekuatan militernya untuk mencuri dan menghancurkan seluruh peninggalan sejarah dan kebudayaan negeri-negeri jajahannya.
Sedikit beruntung, saat itu pihak sekutu membentuk ”tim khusus” yang yang diberikan tugas untuk mencari dan menyelamatkan karya-karya seni dan barang-barang budaya penting lainnya sebelum Nazi menghancurkan atau mencurinya.
Seperti diungkapkan Robertus Robert dalam buku Fernando Báez di atas, perang dan pergantian rezim menjadi dua momentum yang berisiko menempatkan buku di dalam bahaya. Itu artinya perang bukan saja medium dua kubu yang bertemu untuk saling menghabisi, melainkan melibatkan juga beragam alasan kompleks yang salah satunya adalah penguasaan atas sejarah melalui kontrol atas buku-buku.
Di masa Tanah Air, penghancuran buku dikerjakan atas sokongan negara. Di masa Orde Lama tercatat karya Pramoedya Ananta Toer berjudul Hoa Kiau di Indonesia, dan Demokrasi Kita karya Bung Hatta, serta karya-karya lain dari Mochtar Lubis, Sutan Takdir, yang menjadi objek kekerasan terhadap buku.
Meski demikian, baru di Orde Barulah gerakan pelarangan buku dilakukan dengan sistematis dan massif. Dalam hal ini, meminjam analisis Louis Althusser, pemikir Marxis Prancis, negara memerlukan dua perangkat untuk mengkonfirmasi programnya agar berjalan dengan efektif dan efisien di lapangan. Dua aparatus dimaksud, yakni aparatus keras (militer) dan aparatus lunak (lembaga pendidikan, film, dan sastra), sama-sama bertujuan untuk menghiegenisasi alam demokrasi negara dari suara-suara “sumbang” di luar kekuasaan.
Wijaya Herlambang melalui bukunya, Kekerasan Budaya Pasca 1965, dengan apik menjelaskan bagaimana untuk mendukung kegiatan pelarangan buku, negara menggunakan aparatus lunak berupa lembaga-lembaga pendidikan dan kebudayaan demi meneguhkan ideologi dominan negara. Bahkan lebih jauh, agar kekerasan budaya yang ditimbulkan negara mudah diterima dan dianggap sebagai misi bela negara, negara memberikan cukup banyak stok dalil melalui pendidikan, sastra, dan film sebagai medium cuci otaknya.
Implikasinya jelas, pada akhirnya tindakan sepihak untuk melarang, merazia, sampai membakar karya intelektual yang bertentangan dengan negara, masyarakat tidak akan berhadapan dengan dilema moral sama sekali. Alih-alih merasa bersalah, justru tindakan semacam di atas akan dianggap sebagai tindakan heroik yang patut diapresiasi.
Belum lama ini, beredar di lintasan dinding Facebook mengenai razia buku di Kabupaten Pinrang yang diberitakan media setempat sebagai bagian dari gerakan anarko sindikalisme. Di gambar yang mencantumkan akun Satuan Reskrim Pinrang itu menampilkan 8 buah buku, yang 4 di antaranya mencantumkan kata komunisme dan PKI.
Di Tangerang, April lalu, juga lebih awal oleh pihak kepolisian menangkap disinyalir kelompok anarko yang bertujuan ingin membuat keonaran di tengah masa pandemi korona. Sudah seperti skenario klasik, penangkapan itu juga mempertautkan buku sebagai bahan bukti yang seolah-olah berbahaya.
Akhir tahun 2019, kita juga sempat dibuat geram oleh aksi sepihak sekelompok orang yang merazia buku di toko-toko buku. Dalilnya masih sama seperti bagaimana negara menarasikan permusuhannya dengan ideologi komunisme. Semua buku-buku berhaluan marxisme—yang lucunya malah diartikan yang “tertulis” marxisme—berhak dirazia dan diamankan.
Akan banyak daftar hitam pemerintah bertebaran di pemberitaan mengenai tindak tanduk negara yang berkaitan dengan bibliosida. Entah dalam bentuk pelarangan hingga pembumihangusan, buku senantiasa menjadi yang tertuduh dan dicurigai. Pembacanya akan segera dipandang sebagai tersangka alih-alih sebagai seorang pembelajar.
Mengingat bangsa ini mengalami krisis akut di seputar tingkat rendah dan masih minim khazanah kepustakaan, tidak berhentinya sikap permusuhan terhadap buku oleh negara ataupun institusi di bawahnya, adalah sikap kontraproduktif yang akan berefek panjang ke depan.
Buku-buku, entah ia mengandung kontroversi atau sebaliknya, merupakan aset berharga yang mesti dijaga dan dilipatgandakan. Ia mesti menjadi salah satu prioritas di dalam wacana, dan menjadi signifikan di dalam praktik berilmu pengetahuan ketika menangkal kejumudan. Meski musuh-musuh buku baik dalam bentuk rayap menjengkelkan yang siap menghadang dalam kesenyapan almari berdebu, sampai negara yang paling sering pasang badan menjadi agen pemberangus buku.
Malangnya, laporan Báez dalam bukunya di atas bertentangan dengan pendapat umum. Báez menemukan bahwa pelaku kejahatan terhadap buku-buku utamanya bukan dilakukan oleh orang awam yang kurang pendidikan dan pengetahuan, melainkan justru kaum terdidik dengan motif ideologis bermacam-macam. Lebih malang lagi, semua itu diam-diam bagian dari skenario negara tertentu untuk mengontrol rakyatnya dari elan vital roda kekuasaan.
Jangan sampai, suatu waktu nanti, nasib kita akan sama kisahnya seperti para rahib biara Benekdiktin dalam novel epik The Name of The Rose karya Umberto Eco: menjadi jenazah setelah membaca buku-buku terlarang.
Selamat Hari Buku Nasional 17 Mei
2020.